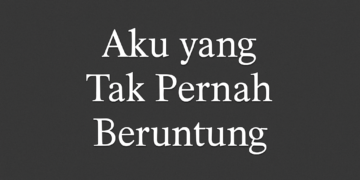Hari itu, seperti hari-hari biasanya, aku berjalan tanpa arah. Langit mendung, tapi anehnya aku merasa lebih mendung di dalam hatiku. Langkahku lambat, seolah menyesap setiap detik yang berlalu, memandangi hidup dari balik kaca yang buram.
Di sudut jalan, aku melihat mereka — anak-anak kecil, berlari sambil memanggul karung yang nyaris lebih besar dari tubuhnya. Mereka memulung, mencari sisa-sisa yang dunia tinggalkan. Tapi yang membuatku terpaku bukanlah karung itu, bukan juga debu yang membalut wajah mereka.
Yang membuatku terdiam adalah tawa mereka — tawa yang jujur, riang, tanpa beban.
Aku berdiri lama, membiarkan hatiku diremukkan oleh pemandangan itu.
Satu sisi aku sedih, sangat sedih. Tapi di sisi lain, aku merasa hangat, melihat bahwa kebahagiaan ternyata bisa hidup di tempat yang paling tidak mungkin.
Aku melangkah lagi, menyusuri deretan pedagang yang hampir semua dagangannya masih utuh di atas meja. Tak banyak pembeli. Angin membawa suara sayup mereka memanggil, menawarkan, berharap. Tapi yang lebih keras kudengar adalah semangat mereka yang tak pernah benar-benar padam.
Mereka tersenyum, berdiri tegak, seolah berkata pada dunia:
“Aku akan bertahan, apa pun yang terjadi.”
Dan di sela hari yang perlahan runtuh itu, aku bertemu dengan seorang teman lama. Matanya penuh lelah, namun bercahaya. Di sampingnya, seorang anak kecil mengenggam erat jari-jarinya. Ia bercerita — tentang malam-malam tanpa tidur, tentang buku-buku penuh coretan, tentang ujian-ujian yang membuatnya hampir menyerah. Semua itu ia jalani demi anaknya. Dan kini, ia berdiri di hadapanku, sebagai seorang PNS yang baru saja diangkat. Sebagai seorang ayah yang menang melawan rasa putus asa.
Aku tersenyum. Aku ikut bahagia untuk mereka.
Bahagia… dan sekali lagi, iri.
Yaaa, iri.
Aku iri pada mereka yang menemukan makna dalam hidupnya.
Aku iri pada mereka yang bisa menangis bahagia atas perjuangannya.
Aku iri pada mereka yang, bahkan dalam keterbatasan, bisa merasa cukup.
Sedangkan aku…
Aku hanya berjalan.
Aku hanya menjalani.
Seperti robot yang diprogram untuk bergerak, tapi tak pernah benar-benar merasa hidup.
Semua orang melihatku dan berkata aku beruntung.
Pekerjaan bagus.
Gaji besar.
Bisa membeli apa saja yang aku mau.
Mereka melihat apa yang tampak, tapi mereka tak pernah bertanya apa yang tersembunyi.
Tak ada yang tahu bahwa aku merasa seperti orang yang tak pernah benar-benar beruntung.
Bukan karena kekurangan materi, bukan karena kegagalan.
Tapi karena ada kekosongan di hati yang tak pernah bisa diisi oleh apa pun yang bisa kubeli.
Aku bersyukur, sungguh aku bersyukur.
Tapi rasa syukur itu tak serta-merta mengusir rasa hampa ini.
Tak serta-merta membuatku merasa cukup.
Tak serta-merta membuatku berhenti bertanya:
“Kapan aku bisa benar-benar merasa hidup?”
“Kapan aku bisa merasakan kebahagiaan yang tidak hanya lewat, tapi tinggal?”
“Kapan aku bisa berhenti merasa menjadi orang yang sekadar hidup?”
Malam itu, di bawah langit yang makin gelap, aku mengangkat wajahku.
Mencoba mencari sesuatu di antara bintang-bintang yang mulai muncul malu-malu.
Aku tak menemukan jawaban.
Tapi mungkin, untuk malam ini, berjalan dan tetap bernapas sudah cukup.
Mungkin, untuk saat ini, sekedar hidup pun, adalah bentuk kecil dari perjuangan.